Oleh : Gayanara
“Kalau begini terus jalan, cepat pasti kita sampai,” kata Akbar, separuh optimistis, separuh bercanda.
Motor kami meluncur di jalan yang sempat mulus menuju Lembah Behoa, Kabupaten Poso. Namun, tak sampai satu menit kemudian, roda kembali menghantam lubang dan bebatuan. Jalan yang tadi dianggap bagus, ternyata hanya sepotong keajaiban sementara. Selebihnya perjuangan panjang di antara lubang dan batu.
Hari itu Minggu, pukul tiga sore, 12 Agustus 2025. Langit Palu masih terang ketika kami memutuskan berangkat menuju salah satu situs megalit paling misterius di Sulawesi Tengah. Lembah Behoa, nama yang belakangan sering muncul di artikel dan dokumenter sejarah, menjadi tujuan utama.
Kami berangkat ber-enam, tiga perempuan dan tiga laki-laki, menunggangi motor menuju dataran tinggi Lore Lindu. Tujuan kami sederhana. Menjejak masa lalu yang membisu dalam batu (Penasaran juga).
Menyusuri Dingin
Perjalanan dari Palu menuju Sigi berjalan lancar, hingga jarum jam menunjuk pukul lima sore. Kami tiba di perbatasan Sigi–Poso, gerbang menuju hutan danau Tambing.
Di sana, udara berubah drastis. Kabut turun perlahan seperti tirai putih yang menutup pandangan. Hawa dingin menyeruak, menembus lapisan pakaian dan jaket yang dipakai.
“Huuuuu… apa ini! Dingin sekali!” teriak Akbar di tengah kabut, suaranya menggema dan menghilang di balik pepohonan
“Dingin sekali,” kata Kailismi.
Kami tertawa, tapi tawa itu menggigil bersama udara tipis di ketinggian.
Sekitar satu jam kemudian, kami tiba di Desa Wuasa, Napu. Sebuah penginapan sederhana bernama Sandi jadi tempat kami bermalam.
Satu kamar kecil kami bagi untuk enam orang. Dua ranjang kecil. Satu untuk para perempuan, satu untuk para pria. Walau berhimpitan, tak ada yang mengeluh. Malam itu kami hanya ingin rebah, menyingkirkan lelah perjalanan.
Setelah makan malam dan berbagi camilan, obrolan ringan menjelma jadi tawa, gosip, dan akhirnya kantuk. Di luar, udara Napu semakin menggigit, tapi di dalam kamar penginapan, tawa kami menghangatkan malam dataran tinggi itu.
Perempuan yang Melompat di Ranjang
Keesokan paginya, sinar matahari dan kabut dingin baru merayap di balik bukit ketika tawa memecah keheningan.
Sri Wulan, salah satu teman kami, melompat-lompat di atas ranjang, berteriak membangunkan yang lain.
“Bangun! Ayo cepat, ini hari petualangan!” katanya dengan semangat berapi-api.
Mata masih berat, tapi semangatnya menular. Kami pun bersiap.Tapi, seperti biasa, persiapan bukan hal cepat bagi tiga rekan perempuan kami.
Bedak, lipstik, dan cermin kecil bergantian mereka pegang seolah itu ritual sebelum perang.
“Tidak usah pakai make-up jauh-jauh. Habis di jalan nanti,” celetuk Rg, satu-satunya dari kami yang sudah pernah ke Behoa sebelumnya.
“Kita ini pigi pesta atau mau kemana,” tambah Egi.
Tapi tentu saja, nasihat itu hanya berakhir sebagai angin lalu. Sebab bagi sebagian orang, perjalanan pun harus tetap cantik.
“Huu. Tnggu tidak lama,” kata Jihan. Perempuan yang selalu memegang erat ritual makeup kemanapun itu.
Ke Behoa
Awal perjalanan pagi itu masih bersahabat. Jalanan rusak tapi bisa dilewati. Kami sempat berpikir, mungkin hanya beberapa kilometer lagi akan membaik. Tapi ternyata kami salah besar.
Jalan ke situs megalit Tadulako penuh lubang dan bebatua. Beruntung hari itu tidak hujan.
Dua jam berlalu, barulah plang bertuliskan “Situs Megalit Tadulako” menyambut kami.
Plang sederhana itu berdiri di Desa Doda, Lore Tengah, di tengah sunyi dan hamparan rumput hijau. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Kami pun berhenti. Di depan kami, terbentang kompleks megalitik yang selama ini hanya kami lihat dari foto, besar, dan penuh misteri.
Situs Megalit Tadulako bukan sekadar tumpukan batu besar. Di sinilah berdiri Arca Tadulako, patung batu yang konon menggambarkan sosok pemimpin atau tokoh penting masa lampau.
Matanya menatap lurus ke depan seolah menyimpan rahasia yang tak mau ia ceritakan. Tak ada penjaga saat kami datang. Hanya sunyi yang menemani. Tapi kawasan ini tampak tertata rapi. Rumputnya dipangkas pendek, beberapa bangunan baru sedang dibangun, mungkin fasilitas wisata.
Kami berjalan di antara batu-batu besar, mencoba menebak apa arti simbol-simbol yang terpahat. Ada kalamba wadah batu raksasa berbentuk silinder, konon digunakan untuk upacara adat atau tempat menyimpan jasad. Ada pula altar batu yang menyerupai meja persembahan.
Batu-batu itu seperti menatap balik, seolah ingin berbicara, tapi dalam bahasa yang sudah lama tak dimengerti manusia.
Hanya lima belas menit kami bertahan di Tadulako. Lalu, kami melanjutkan perjalanan ke situs lain.
Pokekea, di Desa Bariri. Jalan ke sana sedikit lebih baik, dan udara terasa lebih hangat. Di sinilah kami bertemu penjaga situs, lelaki muda dengan senyum ramah yang menyambut pengunjung.
“Iya, banyak pengunjung mengeluh soal jalan,” katanya.
Kami hanya tersenyum. Setelah dua jam berguncang di atas motor, keluhan itu rasanya sudah tak perlu diulang.
Situs Pokekea menyimpan panorama yang luar biasa. Hamparan batu besar berukir tersebar di lahan luas, dikelilingi bukit dan padang rumput. Beberapa batu berbentuk wajah manusia, lainnya menyerupai wadah besar, atau hewan mitologis.
Menurut arkeolog, batu-batu ini berasal dari masa prasejarah, sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi.
Lembah Behoa, bersama Lembah Bada dan Napu, memang dikenal sebagai pusat kebudayaan megalitik tertua di Asia Tenggara. Di sinilah peradaban purba pernah tumbuh, jauh sebelum tulisan dan logam dikenal di Nusantara.
Kami berkeliling cukup lama di Pokekea. Udara lembah berhembus lembut, membuat dedaunan bergoyang seperti berdoa.
‘Wusshhhhh’ Suara desir angin, menciptakn melodi yang anehnya terasa sakral. Kami menatap satu arca besar, wajahnya setengah terhapus waktu.
Entah mengapa, di hadapan batu itu, kami merasa kecil.
“Ini seperti batu Poneglyph yang ada di serial one piece. Itu hanya kartun tapi ini asli. Bagaimana mereka membuatnya pada zaman itu,” ujar Akbar.
Ada semacam kesadaran yang muncul perlahan, bahwa manusia modern, dengan segala kemajuan dan keangkuhannya, hanyalah debu tipis dalam perjalanan waktu panjang bumi ini.
Batu-batu itu masih berdiri, menunggu siapa pun yang mau mendengar cerita mereka. Cerita tentang kehidupan, kematian, dan keabadian.
Menjelang sore, kami pamit.
“Duaaaaarrr” Suara guntur menggema di langit. Menandakan kami harus segera bergegas kembali.
“Ayo pulang sudah ee. Nae asam lambungku,” kata Akbar.
Perjalanan pulang tak kalah berat, tapi entah mengapa terasa lebih ringan. Mungkin karena hati kami sudah penuh dengan kagum dan rasa syukur. Di tengah guncangan jalan berbatu, kami tertawa lagi, menceritakan hal-hal sepele.
Behoa memberi kami banyak hal, rasa lelah, kedinginan, tawa, dan yang paling penting, rasa takjub pada jejak nenek moyang.
Di antara kabut dan bebatuan, kami belajar bahwa sejarah tidak hanya ditulis di buku, tapi juga di batu yang diam dan lembah yang sunyi.
“Saya masih penasaran, bagaimana mereka buat itu batu. Biar jalannya rusak dan jauh. Tapi saya puas, bisa lihat langsung megalit,” kata Kailismi.
Lembah Behoa bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah jendela waktu, tempat kita bisa menatap masa lalu dan memahami betapa kecilnya kita di hadapan sejarah yang berusia ribuan tahun.
Di era modern ini, ketika bangunan megah bisa berdiri dalam semalam dan roboh dalam sekejap, batu-batu Behoa tetap tegak.
Mereka tidak membutuhkan catatan, tidak mengenal kamera, tapi tetap hidup dalam setiap tatapan yang mengagumi mereka. Dan mungkin, seperti kata Akbar di awal perjalanan.
Tapi kini kami tau, perjalanan menuju masa lalu memang tak pernah mudah. Karena setiap jalan menuju sejarah, selalu dipenuhi lubang yang harus kita lewati dengan sabar.
Oh ia, waktu pergi kami juga sempat singgah di Desa Wanga, melihat monumen raja lore dan permaisurinya. Saat perjalanan pulang kembali ke Palu, kami melewati savana. Padang Napu. Pokoknya keren lah.


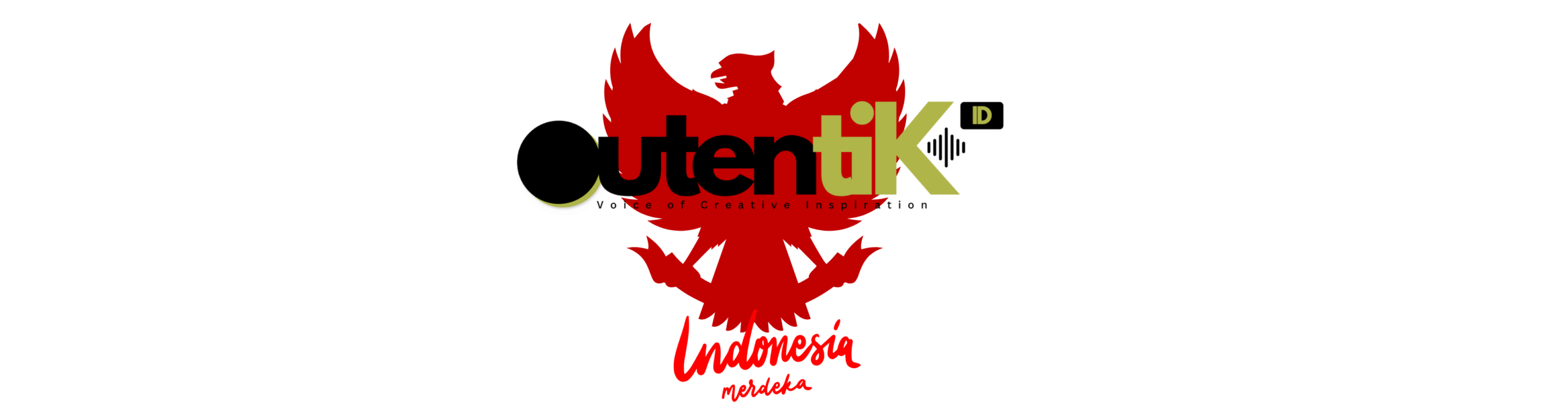







Komentar