OUTENTIK-Dari pinggiran Kota Palu, Kelurahan Nunu tepat pukul lima sore WITA, roda empat open cap mulai bergulir menuju utara, ke sebuah desa yang menanti sunyi bernama Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.
Matahari sore menggantung malas di ufuk barat, mengiringi perjalanan menuju Sisir Pantai Labuana, tempat di mana laut bercerita lewat desah ombak dan pasir menyimpan rahasia malam.
Sekitar pukul sembilan malam, setelah menempuh jalur berliku dalam pelukan senja, kami tiba di bibir pantai. Tanpa banyak jeda, tangan-tangan sigap membangun tenda dan “kalampa”(bangunan sederhana khas masyarakat Kaili, yang biasanya tegak di belakang rumah saat pesta pernikahan. Malam itu, kalampa kami bukan untuk merayakan dua hati yang bersatu, melainkan menjadi saksi pertemuan manusia dengan alam).

Kami memilih sudut pantai yang lebih sunyi, menjauh dari keramaian yang menghidupkan Labuana setiap akhir pekan.
Di bawah langit bertabur bintang, ombak menyanyikan lullaby, dan pasir menjadi alas doa bagi mereka yang ingin sejenak diam dari hiruk pikuk kota.
Bulan malam itu menggantung utuh di langit, memantulkan sinarnya pada permukaan laut, seperti tumpahan perak yang mengalir tenang di atas ombak.
Malam menjadi panggung bagi berbagai peran. Ada yang mendirikan tenda, memancang tiang kecil seperti pelaut membangun dermaga singgah. Ada pula yang menyulut api unggun, menjadikannya lentera kecil pengusir gigil malam.

Asap mengepul menari, membawa aroma sambal balado dan kangkung tumis yang sederhana namun menampar lidah dengan rasa rumah.
Di balik bara api, tawa menyelinap pelan, menghangatkan lebih dari sekadar tubuh. Laut tak henti bersenandung, sementara rindu terhadap alam kian menebal dalam hati masing-masing.
Malam itu, Pantai Labuana bukan hanya sebuah tempat. Ia menjadi pelukan hangat, menjadi ibu yang mendekap anak-anaknya yang pulang sebentar untuk menepi.
Dan bulan, ia menjadi lentera langit yang bersaksi bahwa alam selalu punya cara mengobati letih yang tak sempat terucap.



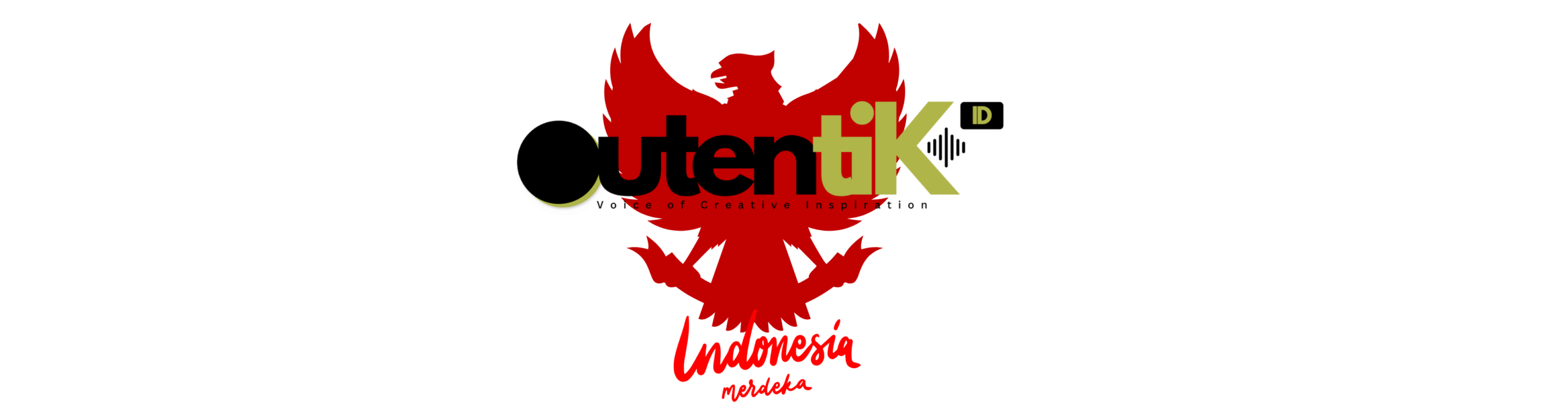







Komentar