Keluarga Tak Sedarah di Bumi Manakarra
Oleh : Gayanara
Langit Makassar seolah berat melepaskan kepergian kami. Rabu, 23 April 2026, adalah hari ketika perjalanan panjang kami berakhir.
Kota yang riuh dengan senyum ramah itu seakan-akan menahan langkah kami saat menjejakkan kaki terakhir di Trans Studio Mall, tempat luas yang nyaris membuat kami tersesat dalam labirin koridor dan lampu-lampu gemerlapnya.
Sore itu, di Terminal Daya, kami berpisah. Ayah mempelai wanita memilih menumpang bus, sedangkan kami setia menunggangi Fazio biru kesayangan, menempuh perjalanan lebih dari 900 kilometer menuju Palu.
Adzan Magrib di kejauhan menjadi aba-aba pertama kami untuk beristirahat. Malam pun menggelayut, dan kantuk akhirnya memaksa kami menepi di Majene.
Waktu menunjukkan pukul 02:30 saat kami menyerah pada lelah, membiarkan mata terpejam di tengah sunyi.
Perjalanan kami lanjutkan esoknya, siang hari 24 April, ketika matahari menghamparkan sinarnya di sepanjang jalur penuh hamparan laut dan ribuan hektar sawit.
Ketika jarum jam menunjuk angka lima sore, kami tiba di Mamuju—kota yang dijuluki Manakarra.
Gerah perjalanan membuat tubuh kami merindu bilasan air. Namun, di tanah asing ini, di mana kami harus bertanya tentang bilik sederhana untuk sekadar mandi? Pantai Manakarra menjadi persinggahan. Kami duduk menikmati pisang goreng hangat, kopi hitam pekat, dan capucino manis sambil menimbang ingatan samar. Kami ingat Kata ayah mempelai wanita, “ada kerabat di Mamuju—rumahnya dekat jembatan, belok kanan ke arah pantai, lima rumah dari ujung,”. ucapnya begitu saja, tanpa penunjuk lebih jelas.
Namun harapan kecil itu kami pupuk. Kami menelusuri Facebook, menggulirkan layar hingga akhirnya menemukan sosok itu: Papa Eka panggilanya. (Nama aslinya dirahasiakan e) heheheh.
Ada sebuah foto dirinya berdiri di depan kios sederhana bertuliskan “KIOS HARAPAN” berbalut warna biru cerah di Jalan Andi Dai.
Tanpa menunggu lama, kami temukan kios itu. Ragu-ragu kami memperkenalkan diri. Awalnya, wajah Papa Eka menyiratkan kebingungan.
Tapi begitu menyadari siapa kami, rona ramahnya menyeruak seperti fajar yang menyibak kabut. Kursi disiapkan, minuman dingin dan roti disuguhkan, seolah kami adalah tamu agung yang telah lama dinanti.
Kami sungkan membuka maksud, tapi keringat dan rasa gerah mengalahkan malu.
Saat kami utarakan niat untuk sekadar membilas badan, Papa Eka tanpa ragu menutup kiosnya dan berkata, “Ayo ayo, rumah di sebelah sana. Disana mandi, makan, minum dulu kita.” ucapnya.
Betapa hangat sambutannya, membuat dada kami sesak haru. Di rumah kecil itu, seorang perempuan dewasa berbaju kuning dan bersarung—Eka namanya—menyambut dengan mata penuh tanya.
Namun seiring percakapan bergulir, benang-benang kenangan pun terjalin, menceritakan masa kecilnya di Palu, bermain di sumur mata air, belajar di sekolah-sekolah yang kini hanya tinggal cerita dalam album kenangan.
Papa Eka pun berkisah tentang masa-masa di Palu dengan penuh semangat.
Ia menyebut satu per satu nama tetangga lama, peristiwa-peristiwa kecil yang ternyata masih terpatri kuat di ingatannya.
Mungkin bukan ingatan semata, pikirku, tapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang telah membekas dalam jiwanya.
Waktu berlalu cepat. Tubuh kami segar, namun perjalanan masih panjang. Dengan berat hati, kami berpamitan.“Om, kami kayaknya mau lanjut perjalanan, sudah mau malam sekali,” ucapku pelan.
“Ha? Mau pulang? Tidak usah dulu, tidur sini saja, besok pagi pulang,” Papa Eka menahan.
Namun kami tetap harus melanjutkan, ada janji dan urusan yang menanti di Palu. Dengan berat hati kami menolak tawarannya.
“Kalau lewat Mamuju lagi, singgah nah,” katanya sambil tersenyum, penuh kehangatan yang sulit digambarkan dengan kata-kata.
Tak banyak waktu memang untuk mengenal seseorang lebih dalam. Tapi terkadang, kebaikan tak butuh waktu panjang untuk dikenali.
Keramahan Papa Eka dan keluarganya adalah pelita kecil yang menyala di sepanjang perjalanan kami.Mereka mungkin berbeda suku, berbeda darah, tapi jiwa mereka telah lama bertaut dalam rasa persaudaraan yang tak lekang dimakan waktu. Seperti bunga-bunga kecil yang tumbuh di antara batu-batu keras, kehangatan itu tetap mekar, melintasi jarak dan masa.


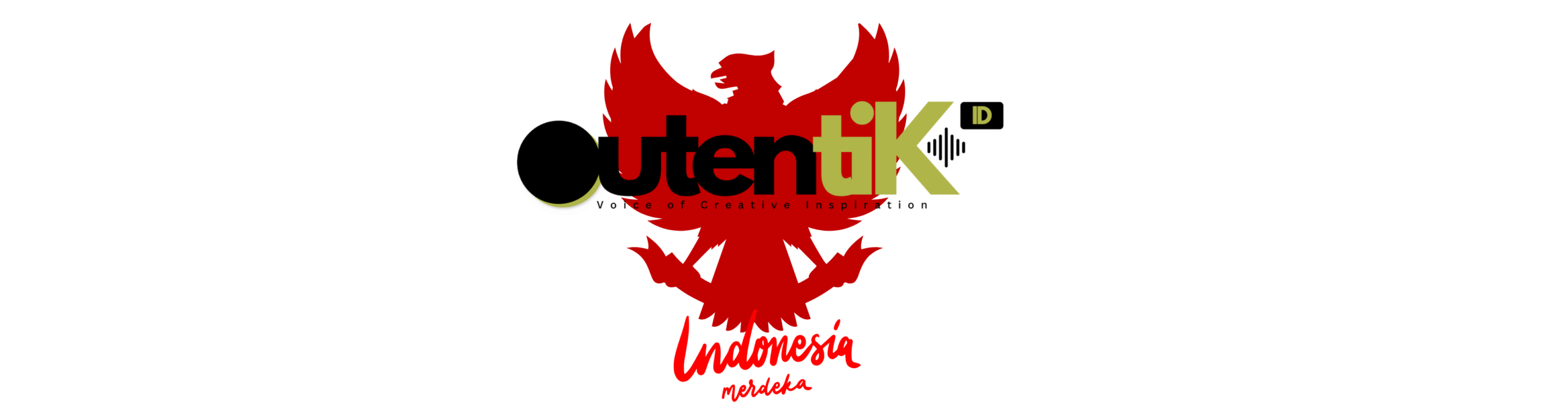







Komentar