By : Gayanara
Langit Palu pagi itu tampak ragu—antara menahan mentari atau membiarkannya menyentuh bumi. Di tengah kecamuk hati dan kantong yang nyaris kosong, kami berdiri di persimpangan niat berangkat atau bertahan.
Makassar menanti, seperti janji lama yang enggan dilupakan. Pesta pernikahan sang adik, bukan sekadar acara, tapi titik temu rasa, keluarga, dan kenangan yang mesti dirangkai.
Modal kami tak seberapa—Rp500.000 saja, cukup untuk segenggam bensin dan sejumput nasi. Tapi semangat kami lebih besar dari angka-angka itu.
Kami percaya, setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan langkah kecil, atau dalam kisah kami satu tarikan gas di atas motor Fazio biru, pada senja tanggal 14 April 2025, yang juga hari ulang tahun ke-61 Sulawesi Tengah.
Sementara kami bersiap, rombongan utama—ayah, ibu, tiga adik dan satu saudara dari pihak ayah—sudah lebih dulu menyusuri aspal yang menggeliat ke selatan.
Kami menyusul selepas magrib, saat langit mulai meredup dan bintang malu-malu mengintip dari balik awan.
Peta bicara tentang 800 kilometer dan 17 jam perjalanan. Tapi waktu tak selalu jujur dalam hitungan. Nyatanya, kami baru tiba di Makassar pukul 04:37 WITA, tanggal 16 April.
Fazio biru itu seolah menyatu dengan tubuh kami, setiap kilometer adalah nyeri dan tawa yang saling berkejaran.
Kami beberapa kali berhenti, sekadar meluruskan pinggang yang pegal atau meneguk kopi murahan di warung tepi jalan.
Pernah, kami tidur beralaskan tikar di pelataran masjid, di mana angin malam bersenandung tentang keberanian.
Makan siang kami temukan di Mamuju, mandi di Majene, lalu terus menembus malam hingga kota Makassar menyambut kami dengan lampu-lampu jalan yang redup dan senyum orang-orang yang tak kami kenal.
Ada sedikit badai kecil saat tiba—salah paham, mungkin karena letih, mungkin karena lapar. Tapi seperti hujan yang tiba-tiba reda, kami pun kembali tertawa, melanjutkan kisah.
Dua hari di Makassar kami habiskan untuk pesta. Adik yang menikah itu, si perajuk manja, ingin semua orang hadir.
Di rumah besar milik kakak ayahnya—kompleks mewah lengkap dengan satpam dan bibi yang cekatan menyajikan makanan hangat—kami tinggal.
Anak-anak di rumah itu ramah, seperti kota yang membuka dirinya perlahan pada kami.
Pesta selesai dengan tangis perpisahan yang lirih. Tapi belum waktunya kami pulang. Mobil keluarga bermasalah, dan beberapa sanak saudara memilih naik bus kembali ke Palu.
Kami tertinggal—berdua, dan ayah dari mempelai wanita. Tak ada pekerjaan, tak ada agenda. Maka kami menjelajahi Makassar: masjid 99 kubah di tengah laut, CPI yang menenangkan, Mal Panakukang yang riuh, coto Makassar yang membakar lidah, dan pisang gepe yang mengejutkan lidah.
Kami belajar menyusup ke logat kota, menyisipkan ki, ji, mi, dan di dalam kalimat, seolah bahasa menjadi jembatan antara kami dan kota ini.
Satu hal tak terlupa: hujan di perjalanan yang merusak LCD ponsel.
Tapi, bukankah setiap perjalanan butuh luka kecil agar menjadi kenangan besar? Hari ini, Jumat 18 April kami masih di Makassar. Menanti untuk kembali ke utara.
Tapi di hati kami, perjalanan ini takkan selesai. Sebab Makassar telah memberi lebih dari sekadar pesta—ia memberi kami cerita.


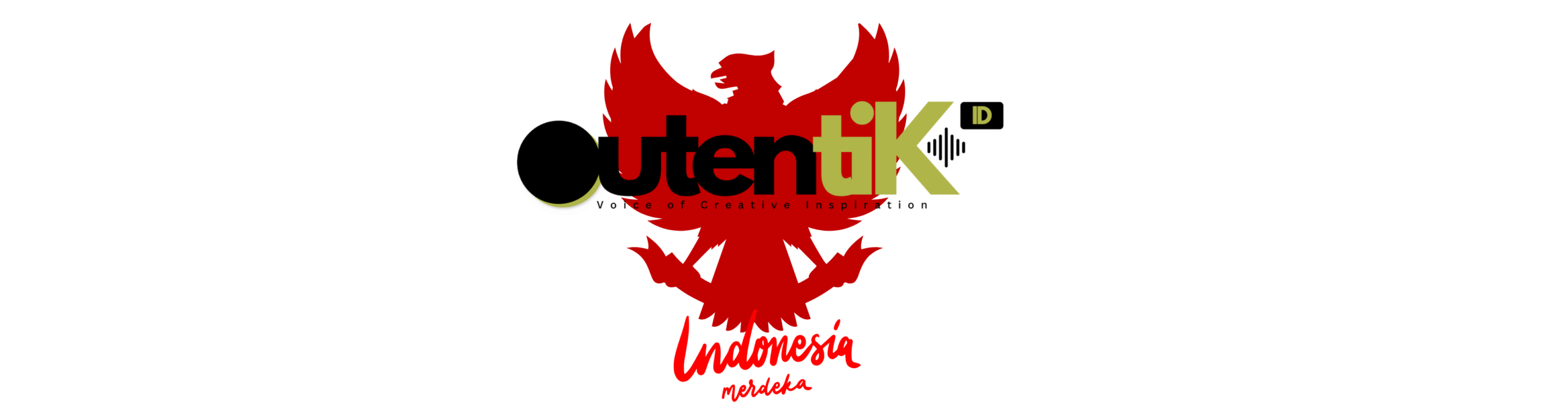







Komentar