Tulisan oleh : Naharudin S.H., M.H
Prolog
Hukum pada hakikatnya berisi konsep-konsep yang lahir dari gagasan, nilai, dan konstruksi berpikir para pembentuk undang-undang. Konsep itu kemudian dituangkan ke dalam rumusan norma yang mengikat. Namun, tidak jarang suatu konsep bersifat multitafsir, tergantung pada konteks penerapannya. Itulah sebabnya, setiap peraturan perundang-undangan biasanya memuat bagian penjelasan umum, untuk mempertegas maksud dan makna dari istilah-istilah hukum yang digunakan di dalam batang tubuh peraturan.
Dalam konteks pembahasan kali ini, istilah “penonaktifan anggota partai politik” menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam, terutama karena istilah ini sering digunakan dalam praktik politik, tetapi tidak dikenal secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan utama yang mengatur kepartaian dan lembaga perwakilan rakyat.
PENONAKTIFAN DAN PEMBERHENTIAN: DUA ISTILAH BERBEDA
Dalam praktik politik dan administrasi partai, dikenal dua istilah yang sering muncul ketika seseorang dijatuhi sanksi organisasi, yaitu penonaktifan dan pemberhentian. Sekilas kedua istilah ini tampak serupa karena sama-sama mengandung makna pembatasan terhadap aktivitas seseorang. Namun secara hukum, keduanya memiliki perbedaan mendasar.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nonaktif berarti tidak aktif, yakni keadaan ketika seseorang atau sesuatu tidak menjalankan tugas, fungsi, atau aktivitas untuk sementara waktu. Dengan demikian, penonaktifan merupakan sanksi bersifat sementara, di mana seseorang tetap berstatus anggota partai, tetapi tidak diberi kewenangan menjalankan fungsi, jabatan, atau hak tertentu untuk jangka waktu tertentu.
Sebaliknya, pemberhentian adalah pencabutan status keanggotaan secara permanen. Artinya, seseorang yang diberhentikan tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan partai politik, baik sebagai anggota biasa maupun sebagai pengurus. Pemberhentian berarti berakhirnya seluruh hak dan kewajiban keanggotaan, termasuk kehilangan legitimasi politik untuk mewakili partai di lembaga publik seperti DPR, DPRD, atau lembaga perwakilan lainnya.
Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan. Penonaktifan tidak menghapus status keanggotaan, sedangkan pemberhentian mengakhiri status tersebut secara total.
KETIADAAN ISTILAH PENONAKTIFAN DALAM UU PARTAI POLITIK DAN UU MD3
Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tidak satu pun di antara ketiga undang-undang tersebut yang menyebut secara eksplisit istilah “penonaktifan” sebagai bentuk sanksi terhadap anggota partai politik.
Dalam Pasal 16A UU Parpol, disebutkan bahwa partai politik berwenang memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar AD/ART, dengan bentuk sanksi yang ditentukan dalam ketentuan internal partai. Namun, diksi “penonaktifan” tidak disebut secara tegas. Begitu pula dalam konteks keanggotaan legislatif, UU Pemilu dan UU MD3 hanya mengenal istilah “pemberhentian” sebagai dasar hukum untuk Pergantian Antar Waktu (PAW).
Dengan demikian, secara normatif, pemberian sanksi “penonaktifan” tidak serta-merta dapat menjadi dasar hukum untuk PAW. Sebab, penonaktifan bukanlah bentuk pemberhentian permanen, melainkan pembatasan sementara yang tidak memutus hubungan hukum keanggotaan.
Dalam konteks keanggotaan DPR atau DPRD, PAW hanya dapat dilakukan apabila seseorang diberhentikan secara tetap dari partainya. Oleh karena itu, penggunaan istilah “penonaktifan” dalam konteks hukum kepartaian harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekeliruan hukum maupun kekacauan administrasi kelembagaan.
ASPEK NORMATIF DAN IMPLIKASI HUKUM
Secara yuridis, penonaktifan anggota partai hanya dapat dianggap sah apabila diatur secara eksplisit dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik. Dengan kata lain, dasar hukumnya bersifat internal dan tidak memiliki dampak langsung terhadap kedudukan seseorang di lembaga publik, kecuali diikuti dengan proses pemberhentian permanen yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Namun dalam praktiknya, sering kali penonaktifan dijadikan alat politik untuk menekan kader atau pejabat publik yang berbeda sikap dengan kepemimpinan partai. Padahal, bila dilihat dari aspek hukum tata negara, status keanggotaan seorang anggota legislatif tidak dapat dicabut hanya karena penonaktifan internal, kecuali partai benar-benar telah melakukan pemberhentian tetap sesuai mekanisme hukum yang sah.
Hal ini penting ditekankan agar partai politik tidak menggunakan istilah “penonaktifan” secara sembrono dan politis, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional anggota. Apalagi dalam sistem demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat dan independensi anggota legislatif harus dijamin, meskipun mereka berasal dari partai tertentu.
Dalam konteks hukum administrasi negara, penonaktifan juga tidak menimbulkan akibat hukum eksternal selama tidak disertai dengan keputusan resmi yang bersifat final dan mengikat. Artinya, seseorang yang dinonaktifkan secara internal tetap memiliki kedudukan hukum sebagai anggota partai dan anggota dewan hingga proses pemberhentian sah dilakukan.
PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah penonaktifan dan pemberhentian memiliki makna dan akibat hukum yang berbeda. Penonaktifan bersifat sementara, tidak menghapus keanggotaan, sedangkan pemberhentian bersifat permanen dan menjadi dasar hukum untuk pergantian antar waktu.
Dengan demikian, bila dikaitkan dengan UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU MD3, maka pemberian sanksi penonaktifan tidak dapat dijadikan dasar untuk PAW. Proses PAW hanya dapat dilakukan jika seseorang telah diberhentikan secara tetap dari keanggotaan partai politik melalui mekanisme yang sah.
Ke depan, partai politik perlu lebih berhati-hati menggunakan istilah hukum dalam proses internalnya. Ketepatan istilah mencerminkan kedewasaan politik dan integritas hukum organisasi. Jika partai ingin menegakkan disiplin, lakukan dengan cara yang patuh pada hukum; jangan justru menambah daftar panjang praktik politik yang mencederai akal sehat demokrasi.
Tentang Penulis
Naharuddin adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu.Ia dikenal sebagai akademisi yang menaruh perhatian pada isu ketatanegaraan, hukum partai politik, dan etika penyelenggara negara


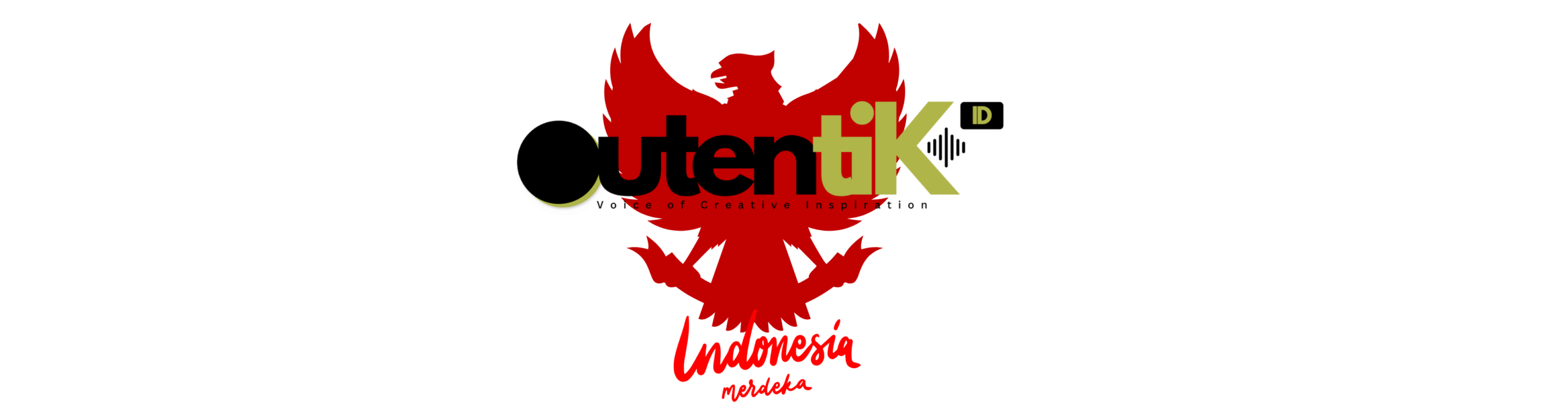







Komentar