“Ee, kamai mai puramo, Kita moende endemo, Moende ka posisani, Ala kita mosisani”
“Ee, randa nte kabilasa Totuatu ante ngana, Moende nte damba lara Ala malindo lara”
Laporan : Gayanara / Outentik.id
Siapa masyarakat Sulawesi Tengah tidak mengenal lagu Posisani. Lagu yang gemanya mengalun di banyak ruang dan waktu, namun sayangnya dan mungkin, nama penciptanya sering tenggelam dalam riuh tepuk tangan.
Hasan Bahasyuan, lelaki asal Parigi Moutong yang sejak muda menanam benih nada dan gerak dalam ibudaya Sulteng, kini kembali dikenang melalui nada-nada yang dirangkai ulang.
Bukan untuk menggantikan, tapi menghidupkan.
Nada Lama dalam Irama Baru, mungkin bisa dibilang seperti itu. Karya karya Hasan Bahasyuan kembali menyala, dinyalakan oleh angin muda bernama The Mangge.
Dalam peluncuran bertajuk A(R)tribute Kick Off, tujuh lagu dari sang maestro budaya Sulawesi Tengah itu dibangkitkan dalam balutan irama modern.
Band The Mangge, anak-anak muda dari Kota Palu, menjadi lentera baru bagi tujuh lagu pusaka Hasan Bahasyuan. Palu Ngataku, Randa Ntovea, Kaili Kana Ku Tora, Putri Balantak, Posisani, Poiri Ngoviana, dan Salandoa.
Lagu-lagu itu bukan sekadar alunan suara, melainkan kearifan Sulteng yang kini dipoles agar lebih bersinar di mata generasi yang tumbuh dengan sentuhan digital dan irama universal.
“Ini bukan sekadar proyek musik, tapi bentuk penghormatan. Kami belajar dari Hasan Bahasyuan, bahwa musik bukan hanya hiburan, tapi juga nyawa dari identitas budaya,” ujar Ryan, personel The Mangge.
Genre yang mereka usungpun bukan untuk mengaburkan maknanya, tapi menjembatani jiwa antar generasi.
The Mangge, group band yang berdiri tegak di tengah riuhnya industri hiburan sejak 2020. Nama mereka bukan sekadar tempelan identitas, tapi nilai-nilai lokal.
The Mangge punya enam jiwa yang membentuk harmoni baru dari Hasan Bahasyuan. Petarung dawai di posisi gitar (Ryan Panintjo) dan bass (Rezha Respati), dua suara yang menjeritkan rasa lewat vokal (Sisca Dama dan Ai Imaji), satu penabuh waktu di drum (Zulkarnaen Ilyas), dan penyihir nada di balik keyboard (Syeren Bawias).
Mereka bukan sekadar memainkan musik, mereka menyalakan warisan, mengangkat lokalitas sebagai roh.
Mereka ingin dunia tahu bahwa dari pelosok pun bisa lahir suara yang menggugah, asalkan akar budaya tetap dijaga.
“Nama the Mangge itu untuk promosi kearifan lokal,” ujar jelasnya.
Zul Fikar Usman, Direktur Hasan Bahasyuan Institut, menyebut langkah ini sebagai bagian dari diplomasi kreatif Indonesia.
Baginya, karya sang maestro bukan hanya milik Sulteng, tapi harta karun bangsa.
“Royalti memang penting, tapi lebih penting lagi adalah menyebutkan nama penciptanya. Kami ingin nama Hasan Bahasyuan lebih besar dari karyanya. Jadi kami minta tolong jika ada yang bawakan lagunya tolong disebutkan penciptanya. Itu saja cukup,” ungkap Zul Fikar.
Ucapan terimakasih juga disampaikan mewakili keluarga besar dan lembaga. “Terimakasih untuk semua pihak yang sudah membantu, terutama untuk Fatur Razaq yang sudah mensupport kegiatan ini,” ucapnya.
Sebuah harapan sederhana tapi bermakna. Untuk menjaga marwah seniman di tengah derasnya arus komersialisasi.
Tercatat, 62 karya Hasan Bahasyuan, mulai dari lagu, taria dan karya lainnya telah diarsipkan resmi di Kementerian Hukum dan HAM.
Angka itu bukan sekadar jumlah, melainkan nadi dari seorang maestro yang menjahit kebudayaan lewat nada, gerak, dan cinta yang tak bertepi untuk tanah kelahirannya.
Hasan Bahasyuan bukan sekadar nama, tapi akar dari pohon besar budaya Sulawesi Tengah. Dari musik bambu, Hawaiian Band, hingga keroncong, ia tanamkan di setiap tanah yang ia jejaki, bahkan hingga ke lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kini, tujuh karyanya kembali menyapa dunia, dalam irama yang berbeda, tapi dengan jiwa yang sama.


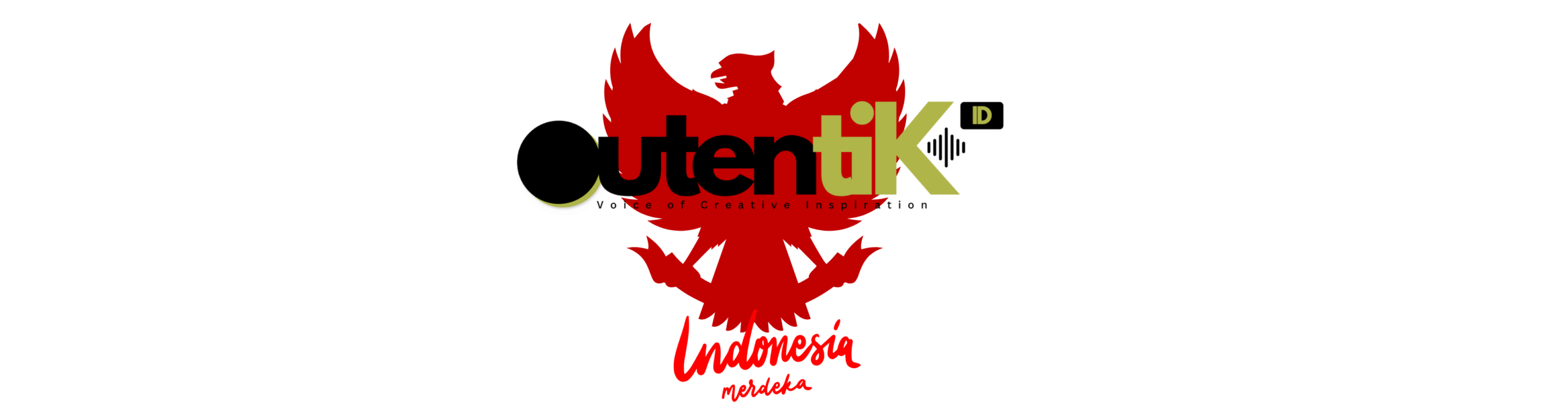







Komentar